Uhm, hari-hari selama Desember ini terasa lebih longgar. Tidak seperti Desember-Desember yang telah lalu. Memasuki Desember ini, hanya ada satu deadline lagi yang perlu kuselesaikan.
Terbiasa dikepung oleh deadline demi deadline, rasanya “aneh” juga ketika terasa memiliki banyak waktu luang begini. Tapi aku jadi punya lebih waktu untuk mengistirahatkan diri. Hanya beban pikiran saja yang tampaknya belum longgar karena ada "proyek" multiyears yang belum selesai.
Untuk “merayakan” kesenggangan itu, aku ingin bercerita tentang sesuatu. Tentang pengemis yang sering kutemui di kedai-kedai kopi.
Kedai kopi selalu menjadi pilihan utamaku untuk bekerja. Kedai kopi favoritku adalah sebuah kedai kopi di daerah kota, persis di tepi Krueng Aceh. Selain tempatnya yang terjangkau dari tempat tinggalku, aku suka citarasa kupi sareng di kedai ini. Seperti hari ini, meskipun aku sudah minum kopi dingin, tetapi rasanya kurang pas kalau belum kena kupi sareng. Alhasil, aku memesan secangkir kopi lagi.
Sudah beberapa jam aku duduk di sini, belum satu pun para peminta itu muncul. Berbeda dengan hari-hari biasa, selama tiga atau empat jam aku di kedai kopi, bisa lebih dari tiga atau empat pengemis yang menyodorkan tangannya. Perempuan, laki-laki, termasuk anak-anak. Belum lagi yang sambil mengamen.
Aku suka mengamati mereka. Cara memintanya macam-macam. Ada yang bermodal ucapan “minta sedekah dikit”; ada juga yang dengan doa-doa. Ada juga yang bermodal ekspresi semata. Tapi lebih banyak cuma modal satu kalimat tadi. Di antara para pengemis yang pernah menyodorkan tangannya ke hadapanku, ada satu yang begitu membekas di ingatanku.
Ia seorang pria. Kutaksir usianya belumlah mencapai lima puluh tahun. Perawakannya sedang, tidak tinggi tidak pendek; tidak kurus tidak juga gemuk. Tampaknya ia pernah terserang stroke ringan sehingga salah satu tangannya terlihat lemah. Saat berjalan pun sebelah kakinya terlihat seperti diseret. Yang melekat dari penampilannya adalah topi jenis flat cap (?) yang sering kulihat dipakai oleh seniman dan tas selempang kecil yang (mungkin) sekaligus berfungsi sebagai dompet.
Biasanya dia akan menghampiri para pengunjung satu demi satu dan saat menyodorkan tangannya tak sepatah kata pun terucap. Ia hanya menyodorkan senyuman. Sebagai pengunjung setia kedai kopi tersebut, bisa dibilang hampir tak pernah aku memberikan sumbangan kepada mereka. Ada beberapa pertimbanganku, di antaranya, kebanyakan yang kulihat memiliki kondisi fisik yang sempurna. Rentang usia mereka pun, meski tak muda lagi, tetapi juga bukan yang tergolong manula yang umumnya berusia di atas 60 tahun. Termasuk si yang bertopi flat cap tadi, hanya pernah kuberi di awal-awal dulu.
Awal November lalu, aku memenuhi undangan diskusi salah seorang rekan ke sebuah kafe. Dibandingkan kedai kopi yang biasa menjadi tongkronganku, kafe itu—sesuai namanya—tergolong elite, baik dari dekorasi dan interiornya, maupun dari variasi dan harga menu-menu yang dijual di sana. Kafe ini terbagi menjadi dua bagian dan bagian depan menghadap ke jalan protokol. Siang atau malam selalu ramai. Satu sisi ruangannya ber-AC dan satu sisi lagi yang lebih luas non-AC. Di tempat yang non-AC ini biasanya lebih ramai para pria karena mereka bisa sambil menghirup lisong.
Malam itu kami duduk di ruang ber-AC. Kebetulan aku duduk menghadap jalan dan posisi ruangan yang non-AC ada di sebelah kiriku. Kedua ruangan ini dibatasi oleh tembok dan pintu kaca yang transparan. Sekonyong-konyong aku melihat sesosok lelaki di seberang sana. Ia duduk dengan posisi menghadap ke ruangan non-AC. Tampaknya ia tidak sendiri, tetapi aku tidak bisa melihat orang yang di depannya karena terhalang tempok.
Laki-laki itu tampaknya sangat menikmati suasana malam itu. Ia duduk di kursi berlapis busa yang dibalut kulit sintetis. Dari telinganya tampak sejulur kabel mini yang menghubungkan ke perangkat digital. Kepalanya agak bergoyang-goyang, persis seperti orang yang sedang menikmati alunan musik. Sesekali tampak seperti merespons pembicaraan dengan orang di hadapannya. Sesekali terlihat tertawa sambil bercakap-cakap. Di hadapannya tersaji sepiring makanan dan segelas minuman. Ekspresinya menyiratkan kalau ia senang dan nyaman.
Aku mengenali orang itu karena sesuatu yang melekat di kepalanya, yaitu topi flat cap. Setelah memperhatikan lebih saksama, benar, memang orang yang sama yang sering aku lihat di kedai kopi tongkronganku. Bedanya kali itu ia sebagai pelanggan, bukan sebagai peminta-minta sebagaimana biasanya. Kenyataan itu membuat aku tak bisa berucap. Ingin tertawa rasanya. Untuk sesaat aku kehilangan fokus.
Berminggu-minggu setelah malam itu, hingga detik aku menuliskan ini, belum sekali pun aku melihat pria dengan topi flat cap itu muncul di kedai kopi ini.[]


















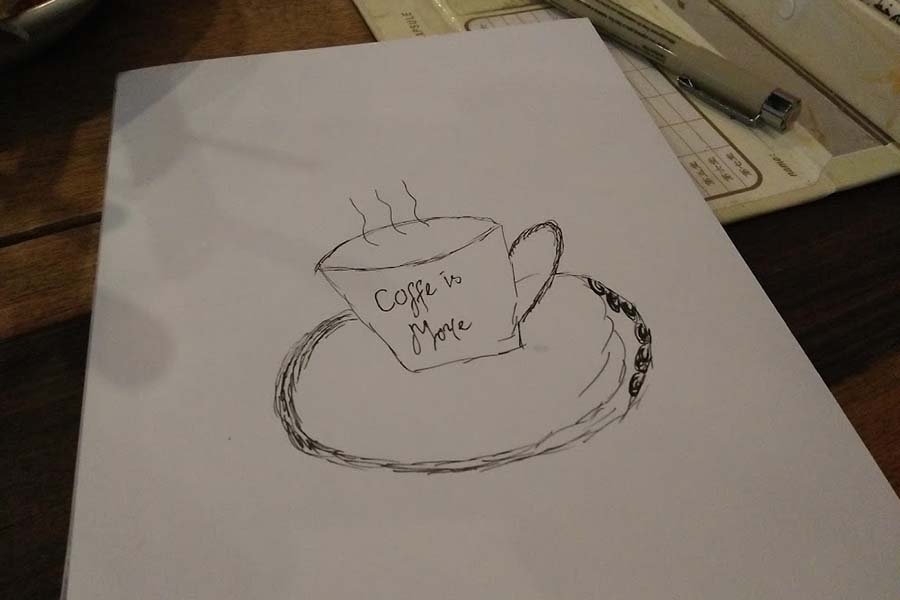












.jpeg)



.jpeg)





